Minggu, 18 Oktober 2009
PERTENTANGAN KASTA DALAM ROMAN AROK DEDES KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER
Oleh : Fredy M.S.B. Wowor, S.S*
PENDAHULUAN
Sastra adalah suatu bentuk gamaran konkret yang merupakan hasil kreasi manusia yang mempesona dan disampaikan dengan menggunakan bahasa. Di dalam sastra tecermin kehidupan manusia, kehidupan ini merupakan refleksi dari keadaan sosial dalam masyarakat (Sumardjo, J dan Saini K. M. 1986 : 3).
Roman merupakan karya sastra yang isinya mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia sepanjang hidupnya sejak lahir, dewasa, bahkan sampai mati.
Arok Dedes adalah sebuah roman sejarah karya Pramoedya Ananta Toer yang diangkat dari kisah sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Roman ini menceritakan perjalan hidup seorang keturunan sudra bernama Arok dan seorang anak brahmana bernama Dedes. Roman ini menceritakan pula perlawanan kaum tertindas yakni rakyat jelata melawan kaum penindas yaitu penguasa. Perlawanan yang dipimpin oleh Arok ini akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung dan menghancurkan pengaruh kerajaan Kediri di Tumapel. Sebuah peristiwa perubahan sosial yang sekarang dikenal sebagai revolusi.
S. N. Eisenstadt mengatakan dalam bukunya, “Revolusi dan Transformasi Masyarakat” bahwa revolusi adalah suatu proses perubahan yang radikal dan mendasar dalam seluruh tatanan kemasyarakatan yang mencakup perubahan kekuasaan pemerintahan dan konsep tatanan sosial. Perubahan sosial ini dilakukan dengan kekerasan (Eisenstadt, 1986 : 6).
Sebuah revolusi terjadi bukan karena kebetulan belaka, tetapi dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di satu negeri.
Dalam bukunya yang berjudul, “Revolusi dan Kontra Revolusi” Karl Marx mengatakan bahwa :
“Setiap kali terjadi ledakan revolusi berarti selalu ada masalah-masalah sosial yang melatar belakanginya.” (Marx, 2000 : 2).
Salah satu masalah sosial yang melandasi terjadinya perubahan sosial yang mendasar atau revolusi yang terungkap dalam roman Arok Dedes ini adalah pertentangan kasta.
PERTENTANGAN KASTA DALAM ROMAN AROK DEDES
Sistem kasta adalah suatu system pengelompokkan sosial yang berdasarkan pembagian kerja yang mengikuti garis keturunan darah. Sistem ini merupakan penyimpangan dari sistem varna yang diformulasikan oleh Manu. Varna adalah sistem pengelompokkan sosial yang berdasarkan pembagian kerja yang mengikuti potensi dan kemampuan setiap orang (Krishna, 1999 : 460).
System kasta mengelompokkan masyarakat dalam beberapa tingkat yaitu kasta brahmana yang terdiri dari para pendeta atau pemimpin agama, kasta ksatria yang terdiri dari para prajurit dan aparat pemerintahan sipil , kasta waisya yang terdiri dari para pedagang, kasta sudra yang terdiri dari para pekerja yakni buruh dan petani. Disamping keempat kasta tersebut terdapat pula suatu kasta yang lain yang kedudukannya lebh rendah dari kasta sudra yaitu kasta paria yang terdiri dari kaum budak (Malaka, 2000 : 10-11).
Sejak masuknya kebudayaan India di Jawa, system kasta pun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, walaupun demikian teori tntang kasta tersebut telah membaur dengan pemahaman masyarakat pribumi pada waktu itu yang membedakannya dari yang berlaku di India (Bosch, 1974 : 17-18).
Dalam tulisannya yang berjudul, ”Sedikit Tentang Golongan-Golongan di Dalam Masyarakat Jawa Kuno” J.G. de Casparis engatakan bahwa ada tiga kelompok yang terpisah-pisah dalam masyarakat jawa kuno yitu yang pertama, kelompok penduduk desa atau rakyat jelata, kedua, kelompok bangsawan yang terdiri dari sang prabu dan keluarganya serta aparat pemerintahnya, ketiga, kelompok agama yang terdiri dari para pendeta atau pemimpin agama (Suleiman, 1985 : 58).
Pada masa pemerintahan Sri Erlangga (1020-1042), system kasta mengalami penyesuaian dan penyederhanaan. Sistemini dikenal dengan nama Triwangsa. Triwangsa terdiri dari brahmana, ksatria dan sudra.
Mengenai hal tersebut Pramoedya Ananta Toer mengemukakan dalam roman Arok Dedes :
“Apapun kekurangan wangsa ini ia mulai mengagumi dharma mereka pada kehidupan, penghapusan kasta waisyia, karena memang tak ada kaum waisyia berdara Hindu. Ia mulai melihat adanya pembagian Triwangsa Erlangga itu secara lebih jelas : kasta brahmana dan satria yang berdarah Hindu dan kasta sudra yang ta mengandung dalam dirinya. Kasta itu tenyata ditentukan oleh darah.” (Toer, 1999:246)
Dalam pelaksanaannya triwangsa tidak secara mutlak berdasarkan pada garis eturunan darah, tetapi lebih didasarkan pada watak dan perbuatan seseorang dalam masyarakat atau dharmanya dalam kehidupan.
Hal ini diungkapkan oleh pramoedya Ananta Toer dalam roman Arok Dedes ini :
“Erlangga pernah menjatuhkan titah : triwangsa bukan hanya ditentukan oleh para dewa, juga manusia bisa melakukan perpindahan kasta karena dharmanya, sudra bisa jadi satria. Sudra bisa jadi brahmana.” (Toer, 1999 : 65).
Berdasarkan penjelasan ini tersebut dapat diketahui bahwa triwangsa pada satu sisi lebih mendekati system varna yang juga ditentukan oleh watak dan perbuatan seseorang dalam masyarakat atau dharmanya dalam kehidupan walaupun pada sisi lain tetap berdasarkan pada pola hirarkisnya pada system kasta (Krishna, 1999 : 460).
Pada masa pemerintahan Sri Kretajaya (1185-1222 M) di Kediri, Triwangsa berpadu dengan perbudakan yang sebelumnya telah dihapuskan oleh Erlangga (Toer, 1999:2).
Adapun Tumapel sebagai daerah jajahan Kediri yang diperintah oleh Tunggul Ametung ikut pula mempraktekkan perbudakan di samping triwangsa. Penindasan terhadap manusia melalui system perbudakan ini telah melahirkan kembali suatu kelompok sosial yang derajatnya serendah binatang dan kedudukannya berada di bawah kasta sudra yaitu kaum paria atau kaum budak.
Kenyataan ini teungkap dalam roman Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer :
“Oti membuang muka. Ia hanya seorang budak, tak mungkin bisa bercampur dengan orang banyak yang bebas. Apalagi menyaksikan orang-orang besar.”
(Toer, 1999:24).
Akuwu Tumapel Tunggul Ametung erupakan seorang keturunan sudra yang berhasil menaikan derajat kastanya dengan menjadi penguasa negeri di Tumapel sehingga berhak memperoleh pengakuan sebagai seorang satria.
Berkuasanya seorangketurunan sudra yang telah disatriakan di Tumapel ini telah menimbulkan ketidakpuasan Yang mendalam di dalam hati para brahmana yang merasa bahwa mereka tidak pantas untuk diperintah oleh satria keturunan sudra ini.
Pertentangan ini terungkap dengan jelas dalam kutipan berikut ini “
“Di sela derap kaki kuda itu terdengar dalam ingatannya suara ayahnya : kaum satria adalah pemukul segala dosa ; dunia akan binasa karena mereka ; dan hanya kaum brahmana bisa selamatkan manusia dan dunia ; maka semua usaha kaum brahmana harus dipusatkan pada kembalinya tata tertib jagad pramudinata.” (Toer, 1999 : 92)
Usaha untuk mengembalikan tata tertib jagad pramudinata ini berarti pemulihan kembali kedudukan kaum brahmana sebagai wakil syiwa di dunia dan untuk itu kaum sudra atau kaum satria harus dikembalikan kepada kedudukannya semula sebagai bawahan dari kaum brahmana (Bosch, 1974 : 29).
Pandangan seorang keturnan brahmana kepada seorang keturunan sudra yang berhasil menaikan derajatnya menjadi satria dapat dilihat pada kutipan berikut :
“Dedes berjalan tanpa kemauan. Ia dengar Yang Suci sekali lagi berbisik menindas :
“Basuhlah kaki yang mulia.”
Darah itu masih saja tak dapat membendung airmatanya dan menangis tersedan-sedan. Ia memprotes entah pada siapa : seorang brahmani yang harus mencuci kaki seorang sudra yang disatriakan oleh Kediri.” (Toer, 1999:10)
Adapun pandangan rendah seorang brahmani terhadap seorang sudra dapat dilihat dari ungkapan Dedes pada kutipan berikut :
“Kau tidak sedungu ayahmu. Kau takkan biki malu ibumu. Kalau kau wanita, kau adalah dewi, kalau kau pria kau adlah dewa. Ayahmu tak punya persangkutan dengan kau. Dengar kau jabang bayi ? Kau berdarah hindu, ayahmu sudra hina.” (1999 : 247)
Pandangan seorang keturunan satria terhadap seorang keturunan sudra yang telah disatriakan dapat dilihat dalam perenungan Kebo ijo seperti terungkap dalam kutipan berikut ini :
“Pikirannya mulai dibuncahi dengan pikiran indah. Tunggul Ametung seorang sudra. Ia anak satria. Ia benarkan Empu Gandring : Sudah semestinya antara Sang Akuwu dan paramesywari tak bakal adakeserasian. Tempat Tunggul Ametung terlalu jauh di bawah Ken Dedes. Dan dirinya sendiri jauh lebih dekat, seorang satria. Juga satria yang selama ini dihinakan oleh Sang Akuwu, tetapi menjadi tamtama, tak bisa lebih tinggi dari seorang kidang yang juga Cuma sudra. Para tamtama lain pun tidak puas dengan sikap Tunggul Ametung, mengetahui para kidang tidak dapat dikatakan tangguh sebagai prajurit.
Ia mengimpikan diri menjungkirka Tunggul Ametung dan dDedes mendampinginya.” (Toer, 1999 : 305)
“Sang Akuwu hanya seorang sudra yang disatriakan. Semua prajuritnya dianggap sudra, tak peduli dia satria, seperti sahaya ini.” (Toer, 1999 : 308)
Berdasarkan kutipan ini dapat diketahui bahwa dalam pandangan kaum satria, kaum sudra yang telah disatriakan tetaplah lebih rendah derajatnya. Hal ini disebabkan oleh garis keturunan mereka yang berasal dari sudra.
Kenyataan ini menunjukan adanya perbedaan pemahaman terhadap kasta dalam praktek triwangsa. Ini menyebabkan makin meruncingnya pertentangan kasta.
Tanggapan kaum sudra terhadap kaum satria dapat dilihat dalam kutipan berikut :
“Ia ingat betul kata-kata Ki Bango Samparan waktu itu :
“Prajurit-prajurit itu ! Kerjanya hanya memburu-buru kita, mengancam kita yang terlambat menyerahkan upeti. Mengapa kau dikejar mereka ?”
Ia menceritakan duduk perkaranya.” (Toer,1999:57)
Adapun pandangan kaum budak terhadap kaum satria yang telah menjerumuskan mereka dalam penderitaan dapat dilihat dalam kutipan berikut ini :
“Dari sebelah barat pasukan si mata satu Mundrayana membawa serta dengannya semua penduduk desa kaki gunung Arjuna, laki dan perempuan, tua dan muda.
Pasukan bekas budak yang mendalam dendamnya terhadap Tunggul Ametung dan barisan jajaro ini, boleh menggunakan panah cepat yang dipelajarinya dari barisan biarawan dan biarawati.”(Toer, 1999:385)
PENUTUP
Berdasarkan seluruh uraian ini dapat disimpulkan bahwa pertentangan kasta yang terjadi antara kasta brahmana, kasta satria, kasta sudra dan paria atau budak akibat praktek triwangsa dan perbudakan pada masa pemerintahan Tunggul Ametung di Tumapel telah mengakibat krisis dalam masyarakat yang berpuncak pada terjadinya perubahan mendasar pada kekuasaan pemerintahan dan tatanan sosial di Tumapel.
DAFTAR PUSTAKA
Bosch, F. D. K. 1974. Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di
Kepulauan Indonesia. Jakarta : bhratara.
Eisenstadt, S. N. 1986. Revolusi dan Transformasi Masyarakat. Jakarta :
Rajawali.
Krishna, A. 1999. Paramhansa Yogananda Otobiografi Seorang Yogi.
Jakarta : Gramedia.
Malaka, T. 2000. Dari Penjara Ke Penjara Bagian Tiga. Jakarta : TePLOK
PRESS.
Marx. K. 2000. Revolusi dan Kontra Revolusi. Yogyakarta : Jendela.
Suleiman, S. 1985. Amerta 2. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Sumardjo, J. dan Saini K. M. 1986. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta :
Gramedia.
Toer, P. A. 1999. Arok Dedes. Jakarta : Hasta Mitra.
*Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakulas Sastra UNSRAT
PENDAHULUAN
Sastra adalah suatu bentuk gamaran konkret yang merupakan hasil kreasi manusia yang mempesona dan disampaikan dengan menggunakan bahasa. Di dalam sastra tecermin kehidupan manusia, kehidupan ini merupakan refleksi dari keadaan sosial dalam masyarakat (Sumardjo, J dan Saini K. M. 1986 : 3).
Roman merupakan karya sastra yang isinya mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia sepanjang hidupnya sejak lahir, dewasa, bahkan sampai mati.
Arok Dedes adalah sebuah roman sejarah karya Pramoedya Ananta Toer yang diangkat dari kisah sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Roman ini menceritakan perjalan hidup seorang keturunan sudra bernama Arok dan seorang anak brahmana bernama Dedes. Roman ini menceritakan pula perlawanan kaum tertindas yakni rakyat jelata melawan kaum penindas yaitu penguasa. Perlawanan yang dipimpin oleh Arok ini akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung dan menghancurkan pengaruh kerajaan Kediri di Tumapel. Sebuah peristiwa perubahan sosial yang sekarang dikenal sebagai revolusi.
S. N. Eisenstadt mengatakan dalam bukunya, “Revolusi dan Transformasi Masyarakat” bahwa revolusi adalah suatu proses perubahan yang radikal dan mendasar dalam seluruh tatanan kemasyarakatan yang mencakup perubahan kekuasaan pemerintahan dan konsep tatanan sosial. Perubahan sosial ini dilakukan dengan kekerasan (Eisenstadt, 1986 : 6).
Sebuah revolusi terjadi bukan karena kebetulan belaka, tetapi dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di satu negeri.
Dalam bukunya yang berjudul, “Revolusi dan Kontra Revolusi” Karl Marx mengatakan bahwa :
“Setiap kali terjadi ledakan revolusi berarti selalu ada masalah-masalah sosial yang melatar belakanginya.” (Marx, 2000 : 2).
Salah satu masalah sosial yang melandasi terjadinya perubahan sosial yang mendasar atau revolusi yang terungkap dalam roman Arok Dedes ini adalah pertentangan kasta.
PERTENTANGAN KASTA DALAM ROMAN AROK DEDES
Sistem kasta adalah suatu system pengelompokkan sosial yang berdasarkan pembagian kerja yang mengikuti garis keturunan darah. Sistem ini merupakan penyimpangan dari sistem varna yang diformulasikan oleh Manu. Varna adalah sistem pengelompokkan sosial yang berdasarkan pembagian kerja yang mengikuti potensi dan kemampuan setiap orang (Krishna, 1999 : 460).
System kasta mengelompokkan masyarakat dalam beberapa tingkat yaitu kasta brahmana yang terdiri dari para pendeta atau pemimpin agama, kasta ksatria yang terdiri dari para prajurit dan aparat pemerintahan sipil , kasta waisya yang terdiri dari para pedagang, kasta sudra yang terdiri dari para pekerja yakni buruh dan petani. Disamping keempat kasta tersebut terdapat pula suatu kasta yang lain yang kedudukannya lebh rendah dari kasta sudra yaitu kasta paria yang terdiri dari kaum budak (Malaka, 2000 : 10-11).
Sejak masuknya kebudayaan India di Jawa, system kasta pun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, walaupun demikian teori tntang kasta tersebut telah membaur dengan pemahaman masyarakat pribumi pada waktu itu yang membedakannya dari yang berlaku di India (Bosch, 1974 : 17-18).
Dalam tulisannya yang berjudul, ”Sedikit Tentang Golongan-Golongan di Dalam Masyarakat Jawa Kuno” J.G. de Casparis engatakan bahwa ada tiga kelompok yang terpisah-pisah dalam masyarakat jawa kuno yitu yang pertama, kelompok penduduk desa atau rakyat jelata, kedua, kelompok bangsawan yang terdiri dari sang prabu dan keluarganya serta aparat pemerintahnya, ketiga, kelompok agama yang terdiri dari para pendeta atau pemimpin agama (Suleiman, 1985 : 58).
Pada masa pemerintahan Sri Erlangga (1020-1042), system kasta mengalami penyesuaian dan penyederhanaan. Sistemini dikenal dengan nama Triwangsa. Triwangsa terdiri dari brahmana, ksatria dan sudra.
Mengenai hal tersebut Pramoedya Ananta Toer mengemukakan dalam roman Arok Dedes :
“Apapun kekurangan wangsa ini ia mulai mengagumi dharma mereka pada kehidupan, penghapusan kasta waisyia, karena memang tak ada kaum waisyia berdara Hindu. Ia mulai melihat adanya pembagian Triwangsa Erlangga itu secara lebih jelas : kasta brahmana dan satria yang berdarah Hindu dan kasta sudra yang ta mengandung dalam dirinya. Kasta itu tenyata ditentukan oleh darah.” (Toer, 1999:246)
Dalam pelaksanaannya triwangsa tidak secara mutlak berdasarkan pada garis eturunan darah, tetapi lebih didasarkan pada watak dan perbuatan seseorang dalam masyarakat atau dharmanya dalam kehidupan.
Hal ini diungkapkan oleh pramoedya Ananta Toer dalam roman Arok Dedes ini :
“Erlangga pernah menjatuhkan titah : triwangsa bukan hanya ditentukan oleh para dewa, juga manusia bisa melakukan perpindahan kasta karena dharmanya, sudra bisa jadi satria. Sudra bisa jadi brahmana.” (Toer, 1999 : 65).
Berdasarkan penjelasan ini tersebut dapat diketahui bahwa triwangsa pada satu sisi lebih mendekati system varna yang juga ditentukan oleh watak dan perbuatan seseorang dalam masyarakat atau dharmanya dalam kehidupan walaupun pada sisi lain tetap berdasarkan pada pola hirarkisnya pada system kasta (Krishna, 1999 : 460).
Pada masa pemerintahan Sri Kretajaya (1185-1222 M) di Kediri, Triwangsa berpadu dengan perbudakan yang sebelumnya telah dihapuskan oleh Erlangga (Toer, 1999:2).
Adapun Tumapel sebagai daerah jajahan Kediri yang diperintah oleh Tunggul Ametung ikut pula mempraktekkan perbudakan di samping triwangsa. Penindasan terhadap manusia melalui system perbudakan ini telah melahirkan kembali suatu kelompok sosial yang derajatnya serendah binatang dan kedudukannya berada di bawah kasta sudra yaitu kaum paria atau kaum budak.
Kenyataan ini teungkap dalam roman Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer :
“Oti membuang muka. Ia hanya seorang budak, tak mungkin bisa bercampur dengan orang banyak yang bebas. Apalagi menyaksikan orang-orang besar.”
(Toer, 1999:24).
Akuwu Tumapel Tunggul Ametung erupakan seorang keturunan sudra yang berhasil menaikan derajat kastanya dengan menjadi penguasa negeri di Tumapel sehingga berhak memperoleh pengakuan sebagai seorang satria.
Berkuasanya seorangketurunan sudra yang telah disatriakan di Tumapel ini telah menimbulkan ketidakpuasan Yang mendalam di dalam hati para brahmana yang merasa bahwa mereka tidak pantas untuk diperintah oleh satria keturunan sudra ini.
Pertentangan ini terungkap dengan jelas dalam kutipan berikut ini “
“Di sela derap kaki kuda itu terdengar dalam ingatannya suara ayahnya : kaum satria adalah pemukul segala dosa ; dunia akan binasa karena mereka ; dan hanya kaum brahmana bisa selamatkan manusia dan dunia ; maka semua usaha kaum brahmana harus dipusatkan pada kembalinya tata tertib jagad pramudinata.” (Toer, 1999 : 92)
Usaha untuk mengembalikan tata tertib jagad pramudinata ini berarti pemulihan kembali kedudukan kaum brahmana sebagai wakil syiwa di dunia dan untuk itu kaum sudra atau kaum satria harus dikembalikan kepada kedudukannya semula sebagai bawahan dari kaum brahmana (Bosch, 1974 : 29).
Pandangan seorang keturnan brahmana kepada seorang keturunan sudra yang berhasil menaikan derajatnya menjadi satria dapat dilihat pada kutipan berikut :
“Dedes berjalan tanpa kemauan. Ia dengar Yang Suci sekali lagi berbisik menindas :
“Basuhlah kaki yang mulia.”
Darah itu masih saja tak dapat membendung airmatanya dan menangis tersedan-sedan. Ia memprotes entah pada siapa : seorang brahmani yang harus mencuci kaki seorang sudra yang disatriakan oleh Kediri.” (Toer, 1999:10)
Adapun pandangan rendah seorang brahmani terhadap seorang sudra dapat dilihat dari ungkapan Dedes pada kutipan berikut :
“Kau tidak sedungu ayahmu. Kau takkan biki malu ibumu. Kalau kau wanita, kau adalah dewi, kalau kau pria kau adlah dewa. Ayahmu tak punya persangkutan dengan kau. Dengar kau jabang bayi ? Kau berdarah hindu, ayahmu sudra hina.” (1999 : 247)
Pandangan seorang keturunan satria terhadap seorang keturunan sudra yang telah disatriakan dapat dilihat dalam perenungan Kebo ijo seperti terungkap dalam kutipan berikut ini :
“Pikirannya mulai dibuncahi dengan pikiran indah. Tunggul Ametung seorang sudra. Ia anak satria. Ia benarkan Empu Gandring : Sudah semestinya antara Sang Akuwu dan paramesywari tak bakal adakeserasian. Tempat Tunggul Ametung terlalu jauh di bawah Ken Dedes. Dan dirinya sendiri jauh lebih dekat, seorang satria. Juga satria yang selama ini dihinakan oleh Sang Akuwu, tetapi menjadi tamtama, tak bisa lebih tinggi dari seorang kidang yang juga Cuma sudra. Para tamtama lain pun tidak puas dengan sikap Tunggul Ametung, mengetahui para kidang tidak dapat dikatakan tangguh sebagai prajurit.
Ia mengimpikan diri menjungkirka Tunggul Ametung dan dDedes mendampinginya.” (Toer, 1999 : 305)
“Sang Akuwu hanya seorang sudra yang disatriakan. Semua prajuritnya dianggap sudra, tak peduli dia satria, seperti sahaya ini.” (Toer, 1999 : 308)
Berdasarkan kutipan ini dapat diketahui bahwa dalam pandangan kaum satria, kaum sudra yang telah disatriakan tetaplah lebih rendah derajatnya. Hal ini disebabkan oleh garis keturunan mereka yang berasal dari sudra.
Kenyataan ini menunjukan adanya perbedaan pemahaman terhadap kasta dalam praktek triwangsa. Ini menyebabkan makin meruncingnya pertentangan kasta.
Tanggapan kaum sudra terhadap kaum satria dapat dilihat dalam kutipan berikut :
“Ia ingat betul kata-kata Ki Bango Samparan waktu itu :
“Prajurit-prajurit itu ! Kerjanya hanya memburu-buru kita, mengancam kita yang terlambat menyerahkan upeti. Mengapa kau dikejar mereka ?”
Ia menceritakan duduk perkaranya.” (Toer,1999:57)
Adapun pandangan kaum budak terhadap kaum satria yang telah menjerumuskan mereka dalam penderitaan dapat dilihat dalam kutipan berikut ini :
“Dari sebelah barat pasukan si mata satu Mundrayana membawa serta dengannya semua penduduk desa kaki gunung Arjuna, laki dan perempuan, tua dan muda.
Pasukan bekas budak yang mendalam dendamnya terhadap Tunggul Ametung dan barisan jajaro ini, boleh menggunakan panah cepat yang dipelajarinya dari barisan biarawan dan biarawati.”(Toer, 1999:385)
PENUTUP
Berdasarkan seluruh uraian ini dapat disimpulkan bahwa pertentangan kasta yang terjadi antara kasta brahmana, kasta satria, kasta sudra dan paria atau budak akibat praktek triwangsa dan perbudakan pada masa pemerintahan Tunggul Ametung di Tumapel telah mengakibat krisis dalam masyarakat yang berpuncak pada terjadinya perubahan mendasar pada kekuasaan pemerintahan dan tatanan sosial di Tumapel.
DAFTAR PUSTAKA
Bosch, F. D. K. 1974. Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di
Kepulauan Indonesia. Jakarta : bhratara.
Eisenstadt, S. N. 1986. Revolusi dan Transformasi Masyarakat. Jakarta :
Rajawali.
Krishna, A. 1999. Paramhansa Yogananda Otobiografi Seorang Yogi.
Jakarta : Gramedia.
Malaka, T. 2000. Dari Penjara Ke Penjara Bagian Tiga. Jakarta : TePLOK
PRESS.
Marx. K. 2000. Revolusi dan Kontra Revolusi. Yogyakarta : Jendela.
Suleiman, S. 1985. Amerta 2. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Sumardjo, J. dan Saini K. M. 1986. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta :
Gramedia.
Toer, P. A. 1999. Arok Dedes. Jakarta : Hasta Mitra.
*Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakulas Sastra UNSRAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



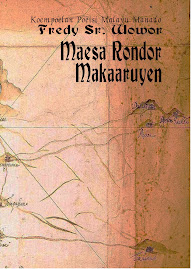
Tidak ada komentar:
Posting Komentar