Minggu, 18 Oktober 2009
MEMBONGKAR WACANA DI BALIK TERMINOLOGI MINAHASA
Karya: Fredy Sreudeman Wowor, SS
Berdasarkan asal katanya “Minahasa” berasal dari kata dasar “Asa” yang berarti satu. Kata “Asa” juga dilafalkan sebagai “Esa”. Melalui lafalan yang tajam dari “S” beserta “A” yang pendek maka kata ini berbunyi seperti “Essa”, “Assa”, seperti “S” telah digandakan. Dengan prefiks “Maha” maka terjadilah kata “Mahasa” berarti menjadi satu atau bersekutu juga berarti telah bersatu. Dengan adanya sisipan “In” terbentuklah kata “Minahasa” yang berarti telah menjadi atau dijadikan satu, persekutuan, persatuan (Grafland, 1987:12).
Kata “Minahasa” mulanya tidak digunakan sebagai sebutan untuk menamai suatu wilayah tapi dipakai untuk menyebut “Rapat Negeri”. Kata ini ditemukan pertama kali dalam surat yang ditulis oleh J.D.Schiersten kepada gubernur Maluku yang bertanggal 8 Oktober 1789 :
“Bij dezen neme ik de Vrijheid Uw WelEdele Achtb
ter g’eerde kennisse te brengen dat de Minhasa of
landraad op den 1 dezer de geschillen tusschen
bantik en Tattelie voigens hunne lands manier hebben
afgedaan staande de solemnisatie of betuiging van
vreede met eede eerstdaags tevolgen”
(Molsbergen, 1928:137)
Artinya:
“Bersama ini saya mengambil kebebasan untuk me-
laporkan dengan hormat kepada paduka tuan,bahwa
Minhasa atau musyawarah para ukung pada tanggal
1 bulan ini,telah menyelesaikan pertikaian antara
Bantik dan Tateli menurut adat istiadat mereka dan
Pengesahan atau pernyataan perdamaian itu akan di-
lakukan kemudian dengan sumpah.”
(Supit,1986:142)
Secara historis sebelum kata “Minahasa” ini dipakai untuk menandai wilayah, telah ada terminologi yang diakui dan diterima serta dipakai untuk menandai keberadaan wilayah yaitu “Malesung” yang artinya “berbentuk seperti lesung”.
Pertanyaannya sekarang mengapa “Minahasa” akhirnya diterima untuk menunjukan keberadaan suatu wilayah yang sebelumnya oleh penduduk pribumi telah dinamai “Malesung” ?
Jawabannya dapat kita telusuri dalam logika Kolonialisme dan Imperialisme yang melandasi cara pandang Kompeni-Belanda yang menganggap Timur (Baca:Malesung) sebagai “Daerah Tak Beradab” yang “Mesti ditaklukan” dan “Dikuasai”. Ini nampak pula dalam usaha penamaan terhadap penduduk pribumi sebagai “Orang Alifuru” atau “Orang Tak Beradab”.
Hal ini jelas menyuratkan kenyataan akan harus adanya “Superioritas” atas “Daerah-daerah tak beradab” itu sehingga dapat “Melegalisasi” setiap proses penaklukan dan eksploitasi yang mereka lakukan.
Alasan lainnya dapat kita lihat dari kenyataan bahwa sejak Simon Cos pelaut Belanda dan pasukannya mendarat di muara sungai Monangolabo (Sungai Tondano) pada tahun 1655 dan mendirikan benteng Nederlandsche Vasticoheit yang kemudian menjadi Benteng Amsterdam Manado, sampai pada Kontrak Persekutuan dan Kerjasama tanggal 10 Januari 1679 pihak Kompeni-Belanda ternyata belum bisa mengadakan pengerukan secara maksimal terhadap sumber daya alam yang ada di tanah Lumimuut-Toar karena adanya perlawanan terhadap kehendak dan kemauan mereka yang dilakukan oleh beberapa walak yang menolak menjual berasnya kepada Kompeni-Belanda, akibatnya adalah terjadinya “Perang Tondano” tahap pertama tahun 1660-1661.
Dari keinginan untuk mendapat untung besar ternyata Kompeni-Belanda malah mengalami kerugian akibat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan selama “Perang Tondano” tahun 1660-1661 tersebut.
Sebab-sebab perang tersebut selain secara mendasar ditentukan oleh adanya konflik kepentingan baik secara ekonomi dan politik juga ditentukan oleh kenyataan bahwa walaupun pihak Kompeni-Belanda telah berhasil mengadakan hubungan dengan beberapa pemimpin walak di tanah Lumimuut-Toar pada waktu itu, tapi ternyata hubungan persahabatan ini tidak berarti bahwa mereka telah dapat mengakses apalagi menguasai seluruh wilayah tanah Lumimuut-Toar yang berada dalam kekuasaan walak-walak lain, sebaliknya mereka malah mengalami perlawanan yang sangat sengit.
Berdasarkan latar belakang kondisi objektif seperti inilah terlahir upaya untuk mendekonstruksi nilai-nilai yang melandasi pola hidup yang membentuk identitas orang-orang keturunan Lumimuut-Toar dan kemudian setelah didekonstruksi nilai-nilai tersebut lalu dikonstruksikan kembali berdasarkan logika Kolonialisme dan Imperialisme untuk mendukung kepentingan Kompeni-Belanda.
Pada tahap ini “Pengkonstruksian Kembali” identitas wilayah dari “Malesung” menjadi “Minahasa” jadi penting artinya karena sebagai “Sebuah wilayah yang telah disatukan” (Oleh Kompeni-Belanda), maka logikanya “Malesung” telah menjadi “Wilayah Jajahan” Kompeni-Belanda. Dan sebagai “Sebuah wilayah yang telah disatukan oleh Kompeni-Belanda”, “Malesung” secara legal formal dapat dieksploitasi untuk kepentingan Kompeni-Belanda.
Bahkan sampai pada zaman ini pun sadar atau tidak kita masih berada dalam bayangan Logika Kolonialisme dan Imperialisme ini sebab sebagian besar informasi yang menyangkut identitas kebangsaan kita orang Malesung berada dalam penguasaan Pemerintah Belanda dan Pemerintah R.I. yang berpusat di Jakarta.
Berdasarkan asal katanya “Minahasa” berasal dari kata dasar “Asa” yang berarti satu. Kata “Asa” juga dilafalkan sebagai “Esa”. Melalui lafalan yang tajam dari “S” beserta “A” yang pendek maka kata ini berbunyi seperti “Essa”, “Assa”, seperti “S” telah digandakan. Dengan prefiks “Maha” maka terjadilah kata “Mahasa” berarti menjadi satu atau bersekutu juga berarti telah bersatu. Dengan adanya sisipan “In” terbentuklah kata “Minahasa” yang berarti telah menjadi atau dijadikan satu, persekutuan, persatuan (Grafland, 1987:12).
Kata “Minahasa” mulanya tidak digunakan sebagai sebutan untuk menamai suatu wilayah tapi dipakai untuk menyebut “Rapat Negeri”. Kata ini ditemukan pertama kali dalam surat yang ditulis oleh J.D.Schiersten kepada gubernur Maluku yang bertanggal 8 Oktober 1789 :
“Bij dezen neme ik de Vrijheid Uw WelEdele Achtb
ter g’eerde kennisse te brengen dat de Minhasa of
landraad op den 1 dezer de geschillen tusschen
bantik en Tattelie voigens hunne lands manier hebben
afgedaan staande de solemnisatie of betuiging van
vreede met eede eerstdaags tevolgen”
(Molsbergen, 1928:137)
Artinya:
“Bersama ini saya mengambil kebebasan untuk me-
laporkan dengan hormat kepada paduka tuan,bahwa
Minhasa atau musyawarah para ukung pada tanggal
1 bulan ini,telah menyelesaikan pertikaian antara
Bantik dan Tateli menurut adat istiadat mereka dan
Pengesahan atau pernyataan perdamaian itu akan di-
lakukan kemudian dengan sumpah.”
(Supit,1986:142)
Secara historis sebelum kata “Minahasa” ini dipakai untuk menandai wilayah, telah ada terminologi yang diakui dan diterima serta dipakai untuk menandai keberadaan wilayah yaitu “Malesung” yang artinya “berbentuk seperti lesung”.
Pertanyaannya sekarang mengapa “Minahasa” akhirnya diterima untuk menunjukan keberadaan suatu wilayah yang sebelumnya oleh penduduk pribumi telah dinamai “Malesung” ?
Jawabannya dapat kita telusuri dalam logika Kolonialisme dan Imperialisme yang melandasi cara pandang Kompeni-Belanda yang menganggap Timur (Baca:Malesung) sebagai “Daerah Tak Beradab” yang “Mesti ditaklukan” dan “Dikuasai”. Ini nampak pula dalam usaha penamaan terhadap penduduk pribumi sebagai “Orang Alifuru” atau “Orang Tak Beradab”.
Hal ini jelas menyuratkan kenyataan akan harus adanya “Superioritas” atas “Daerah-daerah tak beradab” itu sehingga dapat “Melegalisasi” setiap proses penaklukan dan eksploitasi yang mereka lakukan.
Alasan lainnya dapat kita lihat dari kenyataan bahwa sejak Simon Cos pelaut Belanda dan pasukannya mendarat di muara sungai Monangolabo (Sungai Tondano) pada tahun 1655 dan mendirikan benteng Nederlandsche Vasticoheit yang kemudian menjadi Benteng Amsterdam Manado, sampai pada Kontrak Persekutuan dan Kerjasama tanggal 10 Januari 1679 pihak Kompeni-Belanda ternyata belum bisa mengadakan pengerukan secara maksimal terhadap sumber daya alam yang ada di tanah Lumimuut-Toar karena adanya perlawanan terhadap kehendak dan kemauan mereka yang dilakukan oleh beberapa walak yang menolak menjual berasnya kepada Kompeni-Belanda, akibatnya adalah terjadinya “Perang Tondano” tahap pertama tahun 1660-1661.
Dari keinginan untuk mendapat untung besar ternyata Kompeni-Belanda malah mengalami kerugian akibat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan selama “Perang Tondano” tahun 1660-1661 tersebut.
Sebab-sebab perang tersebut selain secara mendasar ditentukan oleh adanya konflik kepentingan baik secara ekonomi dan politik juga ditentukan oleh kenyataan bahwa walaupun pihak Kompeni-Belanda telah berhasil mengadakan hubungan dengan beberapa pemimpin walak di tanah Lumimuut-Toar pada waktu itu, tapi ternyata hubungan persahabatan ini tidak berarti bahwa mereka telah dapat mengakses apalagi menguasai seluruh wilayah tanah Lumimuut-Toar yang berada dalam kekuasaan walak-walak lain, sebaliknya mereka malah mengalami perlawanan yang sangat sengit.
Berdasarkan latar belakang kondisi objektif seperti inilah terlahir upaya untuk mendekonstruksi nilai-nilai yang melandasi pola hidup yang membentuk identitas orang-orang keturunan Lumimuut-Toar dan kemudian setelah didekonstruksi nilai-nilai tersebut lalu dikonstruksikan kembali berdasarkan logika Kolonialisme dan Imperialisme untuk mendukung kepentingan Kompeni-Belanda.
Pada tahap ini “Pengkonstruksian Kembali” identitas wilayah dari “Malesung” menjadi “Minahasa” jadi penting artinya karena sebagai “Sebuah wilayah yang telah disatukan” (Oleh Kompeni-Belanda), maka logikanya “Malesung” telah menjadi “Wilayah Jajahan” Kompeni-Belanda. Dan sebagai “Sebuah wilayah yang telah disatukan oleh Kompeni-Belanda”, “Malesung” secara legal formal dapat dieksploitasi untuk kepentingan Kompeni-Belanda.
Bahkan sampai pada zaman ini pun sadar atau tidak kita masih berada dalam bayangan Logika Kolonialisme dan Imperialisme ini sebab sebagian besar informasi yang menyangkut identitas kebangsaan kita orang Malesung berada dalam penguasaan Pemerintah Belanda dan Pemerintah R.I. yang berpusat di Jakarta.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



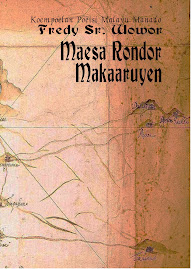
Tidak ada komentar:
Posting Komentar